Judul : Tanah Tabu
Penulis : Anindita S. Thayf
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : kedua, November 2015
Tebal : 240 halaman
“Perusahaan di ujung jalan itu hanya setia pada emas kita. Tidak peduli apakah tanah air, dan orang-orang kita jadi rusak karenanya, yang penting semua emas punya mereka. Mereka jadi kaya, kita ditinggal miskin. Miskin di tanah sendiri!”
Oleh: Mujawaroh Annafi
Dalam berbagai konflik dan penindasan, tak jarang kaum perempuan menunjukkan perlawanan sebagai penegasan bahwa perempuan tak layak dipandang sebagai jender kelas dua. Konflik yang sedang memanas antara masyarakat pegunungan Kendeng, Jawa Tengah dengan pihak PT Semen Indonesia, contohnya, memperlihatkan begitu dominannya perlawanan kaum perempuan menolak pembangunan pabrik semen. Keruan saja, sebab perempuan adalah pihak pertama yang paling merasakan dampak pengrusakan alam oleh korporasi.
Eksploitasi pegunungan karst tersebut jelas akan menghilangkan sumber air yang dibutuhkan untuk urusan mereka dalam rumah tangga seperti mencuci dan memasak hingga untuk bertani dan beternak, dua mata pencarian utama masyarakat Kendeng yang juga melibatkan perempuan sebagai pekerjanya.
Jika perempuan Kendeng melakukan perlawanan atas dasar menjaga sumber kebutuhan vital kehidupan mereka, di timur Indonesia, kaum perempuan, tanpa sorotan media, barangkali juga melakukan perlawanan atas penindasan bernama sistem patriarki yang sesungguhnya berkait-kelindan dengan berdirinya perusahaan tambang emas di sana, yang keberadaanya tak memberikan kesejahteraan bagi penduduk Papua, alih-alih justru menimbulkan masalah sosial dan berbagai bentuk penindasan. Anindita S Thayf menuliskan kisah penderitaan dan perlawanan perempuan Papua, yang tertindas oleh budaya patriarki dan kekuasaan.
Novel ini berkisah tentang tiga orang perempuan Papua suku Dani yaitu Mama Anabel yang akrab disapa Mabel, Mace Lisbeth menantu Mabel serta Leksi cucu Mabel yang masih berusia tujuh tahun. Ada juga tokoh lain yaitu Pum sahabat Mabel sejak kecil, Kwee yang setia menjaga Leksi serta tetangga Mabel, Mama Helda dan anaknya Yosi.
Dalam novel ini cerita lebih dominan terhadap Mabel. Mabel diceritakan sebagai sosok perempuan kuat yang menolak penindasan kaum laki-laki, menolak politik yang hanya mengutamakan perut sendiri, juga menolak penjajahan tak langsung dari orang asing yang hidup di atas tanah emas Papua.
Kerasnya kehidupan yang pernah Mabel jalani menjadikannya wanita yang berpikiran terbuka, cerdas dan berani mengungkapkan hal yang dianggapnya benar dan menolak segala bentuk penindasan oleh siapa pun. Meskipun tak pernah mengenyam bangku pendidikan, Mabel bisa membaca, menulis, dan berbahasa asing.
Ketika menginjak remaja Mabel menjadi pembantu sebuah keluarga Belanda yang baik hati. Di situlah ia belajar dan menjadi gadis Papua yang berpikiran maju. Kegemarannya membaca membuka pikirannya tentang berbagai pengetahuan yang sebelumnya tak pernah ia dapatkan.
Namun, ketika keluarga Belanda itu kembali ke negeri asalnya, kembalilah pula Mabel ke kehidupan kelamnya, kembali ke kampung halaman dan menikah. Dua kali pernikahannya gagal. Ia juga sempat diculik dan dituduh bersekongkol dengan kelompok separatis serta dianggap pemberontak. Karena itulah ia disiksa dengan siksaan, yang binatang pun tak layak mendapatkannya oleh orang-orang berseragam militer, yang sering melakukan teror dan pembantaian terhadap orang-orang Papua.
Semua pengalaman baik dan buruk yang Mabel dapatkan menjadikannya wanita tegar yang disegani, bahkan oleh pria sekalipun.
Karena Mabel jugalah suara perempuan yang hanya terdengar nyaris seperti bisikan menjadi terdengar lantang di telinga semua orang. Mabel tak hanya dikenal pemberani tapi juga perempuan idealis yang sangat kritis terhadap segala bentuk pembodohan yang dilakukan berbagai pihak.
Begitu banyak ketimpangan-ketimpangan yang ingin diungkapkan penulis melalui novel ini, patriarki, kekuasaan, harta, politik hingga rumah tangga, semua diceritakan secara gamblang dari berbagai sudut pandang semua tokoh-tokoh dalam novel ini.
Tidur beralaskan emas, tetapi rakyat Papua justru tambah menderita, kelaparan, miskin dan penyakitan. Hutan tak lagi menghasilkan sagu, sedangkan sungai pun tercemar limbah perusahaan emas di ujung jalan sana. Datangnya investor asing ke Tanah Papua memang membawa perubahan dan modernisasi. Mereka mendirikan perusahaan, namun itu semua tak banyak memberikan manfaat bagi penduduk asli. Tambang emas yang terus-menerus digali, tempat yang dulunya asri telah berubah seiring kemodernan yang ditawarkan orang-orang asing tersebut.
Mabel menganggap kemiskinan di Tanah Papua juga tidak lepas dari peran orang-orang asing tersebut yang juga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan sosial, meningkatnya patriarki di mana penindasan wanita oleh laki-laki menjadi hal yang biasa, seolah-olah perempuan diciptakan untuk menyenangkan hati suami dengan menjadi wanita yang mengorbankan sisa hidupnya demi keluarga, suami, kebun, dan babi.
Kemiskinan mengantarkan para pria untuk melampiaskan kekesalan, kekecewaannya kepada keluarganya di rumah. Pria Komen, sebutan untuk lelaki asli Papua adalah pria perkasa yang gagah berani, mereka menganggap wanita adalah makhluk yang lemah sehingga layak untuk dilindungi. Mati-matian mereka korbankan hidupnya demi wanita apabila diganggu oleh suku lain, tapi mati-matian pula mereka menghajar istrinya tergantung suasana hati.
Semakin miskin laki-laki semakin keras ia bekerja. Tapi semakin banyak ia mendapatkan uang dari bekerja maka semakin parah mereka menenggak arak. Imbasnya, anak istri di rumah yang tersiksa.
Baik Mabel ataupun Mace sama-sama pernah mengalami penindasan oleh kaum laki-laki, tapi Mabel memutuskan untuk melepaskan takdir yang membelenggunya. Dikatakannya kepada Mace untuk keluar dari kebodohan yang menjadi akar permasalahan kaum wanita. Bersama-sama mereka berdua menyekolahkan Leksi agar tumbuh menjadi wanita yang cerdas dan tidak terbelenggu oleh takdir yang dikatakan adat. Kepada Leksi Mabel berujar, “ketahuilah, Nak. Rasa takut adalah awal dari kebodohan – jangan sekali-kali engkau memandangnya dengan sebelah mata – mampu membuat siapa pun dilupakan kodratnya sebagai manusia.”
Pengalaman mengajarkan Mabel untuk tidak mudah percaya pada janji-janji manis politikus. Sebagai seorang wanita yang berpengaruh ia banyak mendapatkan bujuk rayuan di musim pilkada. Tak segan-segan ia menolak terang-terangan calon-calon bermulut manis yang mengetuk pintu rumahnya sambil membawa kaos berwarna-warni. Tanpa Mabel sadari tindakannya membuat ia dijebak dan membuatnya kembali dicap sebagai pemberontak. Lagi, ia dijemput lantas diinterogasi seraya disiksa oleh tentara Indonesia.
Ini memang hanya fiksi, tapi berangkat dari realitas. Mungkin tak banyak yang mau tahu bagaimana nasib Mabel-Mabel dan Leksi-Leksi lain yang tinggal di sana. Yang jelas, perlawanan melawan penindasan dari satu pihak terhadap pihak lain harus terus diperjuangkan.
Novel ini sarat akan pesan kritik sosial, menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca. Penulis mengambil sudut pandang dari setiap tokoh dalam novel Tanah Tabu ini sehingga pembaca tidak hanya melihat kejadian dari satu sudut pandang narator. Lebih kerennya lagi, penulis tidak hanya meletakkan manusia sebagai narator, pembaca tidak akan menyadari sebelum sampai di akhir cerita bahwa kisah kehidupan Mabel dan keluarganya juga diceritakan oleh tokoh yang bukan manusia. Namun pengambilan sudut pandang yang berganti-gantian acap kali membuat pembaca lupa siapa yang sedang bercerita.
Gaya bercerita yang unik, komposisi yang menarik, juga urgensi masalah menjadikan Tanah Tabu juara pertama dalam Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2008, dengan dewan juri diantaranya dua sastrawan cum jurnalis kondang Linda Christanti dan Seno Gumira Ajidarma, sehingga tentu saja novel ini layak dan bagus untuk dimasukkan dalam daftar baca anda.
Penulis : Anindita S. Thayf
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : kedua, November 2015
Tebal : 240 halaman
“Perusahaan di ujung jalan itu hanya setia pada emas kita. Tidak peduli apakah tanah air, dan orang-orang kita jadi rusak karenanya, yang penting semua emas punya mereka. Mereka jadi kaya, kita ditinggal miskin. Miskin di tanah sendiri!”
Oleh: Mujawaroh Annafi
Dalam berbagai konflik dan penindasan, tak jarang kaum perempuan menunjukkan perlawanan sebagai penegasan bahwa perempuan tak layak dipandang sebagai jender kelas dua. Konflik yang sedang memanas antara masyarakat pegunungan Kendeng, Jawa Tengah dengan pihak PT Semen Indonesia, contohnya, memperlihatkan begitu dominannya perlawanan kaum perempuan menolak pembangunan pabrik semen. Keruan saja, sebab perempuan adalah pihak pertama yang paling merasakan dampak pengrusakan alam oleh korporasi.
Eksploitasi pegunungan karst tersebut jelas akan menghilangkan sumber air yang dibutuhkan untuk urusan mereka dalam rumah tangga seperti mencuci dan memasak hingga untuk bertani dan beternak, dua mata pencarian utama masyarakat Kendeng yang juga melibatkan perempuan sebagai pekerjanya.
Jika perempuan Kendeng melakukan perlawanan atas dasar menjaga sumber kebutuhan vital kehidupan mereka, di timur Indonesia, kaum perempuan, tanpa sorotan media, barangkali juga melakukan perlawanan atas penindasan bernama sistem patriarki yang sesungguhnya berkait-kelindan dengan berdirinya perusahaan tambang emas di sana, yang keberadaanya tak memberikan kesejahteraan bagi penduduk Papua, alih-alih justru menimbulkan masalah sosial dan berbagai bentuk penindasan. Anindita S Thayf menuliskan kisah penderitaan dan perlawanan perempuan Papua, yang tertindas oleh budaya patriarki dan kekuasaan.
Novel ini berkisah tentang tiga orang perempuan Papua suku Dani yaitu Mama Anabel yang akrab disapa Mabel, Mace Lisbeth menantu Mabel serta Leksi cucu Mabel yang masih berusia tujuh tahun. Ada juga tokoh lain yaitu Pum sahabat Mabel sejak kecil, Kwee yang setia menjaga Leksi serta tetangga Mabel, Mama Helda dan anaknya Yosi.
Dalam novel ini cerita lebih dominan terhadap Mabel. Mabel diceritakan sebagai sosok perempuan kuat yang menolak penindasan kaum laki-laki, menolak politik yang hanya mengutamakan perut sendiri, juga menolak penjajahan tak langsung dari orang asing yang hidup di atas tanah emas Papua.
Kerasnya kehidupan yang pernah Mabel jalani menjadikannya wanita yang berpikiran terbuka, cerdas dan berani mengungkapkan hal yang dianggapnya benar dan menolak segala bentuk penindasan oleh siapa pun. Meskipun tak pernah mengenyam bangku pendidikan, Mabel bisa membaca, menulis, dan berbahasa asing.
Ketika menginjak remaja Mabel menjadi pembantu sebuah keluarga Belanda yang baik hati. Di situlah ia belajar dan menjadi gadis Papua yang berpikiran maju. Kegemarannya membaca membuka pikirannya tentang berbagai pengetahuan yang sebelumnya tak pernah ia dapatkan.
Namun, ketika keluarga Belanda itu kembali ke negeri asalnya, kembalilah pula Mabel ke kehidupan kelamnya, kembali ke kampung halaman dan menikah. Dua kali pernikahannya gagal. Ia juga sempat diculik dan dituduh bersekongkol dengan kelompok separatis serta dianggap pemberontak. Karena itulah ia disiksa dengan siksaan, yang binatang pun tak layak mendapatkannya oleh orang-orang berseragam militer, yang sering melakukan teror dan pembantaian terhadap orang-orang Papua.
Semua pengalaman baik dan buruk yang Mabel dapatkan menjadikannya wanita tegar yang disegani, bahkan oleh pria sekalipun.
Karena Mabel jugalah suara perempuan yang hanya terdengar nyaris seperti bisikan menjadi terdengar lantang di telinga semua orang. Mabel tak hanya dikenal pemberani tapi juga perempuan idealis yang sangat kritis terhadap segala bentuk pembodohan yang dilakukan berbagai pihak.
Begitu banyak ketimpangan-ketimpangan yang ingin diungkapkan penulis melalui novel ini, patriarki, kekuasaan, harta, politik hingga rumah tangga, semua diceritakan secara gamblang dari berbagai sudut pandang semua tokoh-tokoh dalam novel ini.
Tidur beralaskan emas, tetapi rakyat Papua justru tambah menderita, kelaparan, miskin dan penyakitan. Hutan tak lagi menghasilkan sagu, sedangkan sungai pun tercemar limbah perusahaan emas di ujung jalan sana. Datangnya investor asing ke Tanah Papua memang membawa perubahan dan modernisasi. Mereka mendirikan perusahaan, namun itu semua tak banyak memberikan manfaat bagi penduduk asli. Tambang emas yang terus-menerus digali, tempat yang dulunya asri telah berubah seiring kemodernan yang ditawarkan orang-orang asing tersebut.
Mabel menganggap kemiskinan di Tanah Papua juga tidak lepas dari peran orang-orang asing tersebut yang juga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan sosial, meningkatnya patriarki di mana penindasan wanita oleh laki-laki menjadi hal yang biasa, seolah-olah perempuan diciptakan untuk menyenangkan hati suami dengan menjadi wanita yang mengorbankan sisa hidupnya demi keluarga, suami, kebun, dan babi.
Kemiskinan mengantarkan para pria untuk melampiaskan kekesalan, kekecewaannya kepada keluarganya di rumah. Pria Komen, sebutan untuk lelaki asli Papua adalah pria perkasa yang gagah berani, mereka menganggap wanita adalah makhluk yang lemah sehingga layak untuk dilindungi. Mati-matian mereka korbankan hidupnya demi wanita apabila diganggu oleh suku lain, tapi mati-matian pula mereka menghajar istrinya tergantung suasana hati.
Semakin miskin laki-laki semakin keras ia bekerja. Tapi semakin banyak ia mendapatkan uang dari bekerja maka semakin parah mereka menenggak arak. Imbasnya, anak istri di rumah yang tersiksa.
Baik Mabel ataupun Mace sama-sama pernah mengalami penindasan oleh kaum laki-laki, tapi Mabel memutuskan untuk melepaskan takdir yang membelenggunya. Dikatakannya kepada Mace untuk keluar dari kebodohan yang menjadi akar permasalahan kaum wanita. Bersama-sama mereka berdua menyekolahkan Leksi agar tumbuh menjadi wanita yang cerdas dan tidak terbelenggu oleh takdir yang dikatakan adat. Kepada Leksi Mabel berujar, “ketahuilah, Nak. Rasa takut adalah awal dari kebodohan – jangan sekali-kali engkau memandangnya dengan sebelah mata – mampu membuat siapa pun dilupakan kodratnya sebagai manusia.”
Pengalaman mengajarkan Mabel untuk tidak mudah percaya pada janji-janji manis politikus. Sebagai seorang wanita yang berpengaruh ia banyak mendapatkan bujuk rayuan di musim pilkada. Tak segan-segan ia menolak terang-terangan calon-calon bermulut manis yang mengetuk pintu rumahnya sambil membawa kaos berwarna-warni. Tanpa Mabel sadari tindakannya membuat ia dijebak dan membuatnya kembali dicap sebagai pemberontak. Lagi, ia dijemput lantas diinterogasi seraya disiksa oleh tentara Indonesia.
Ini memang hanya fiksi, tapi berangkat dari realitas. Mungkin tak banyak yang mau tahu bagaimana nasib Mabel-Mabel dan Leksi-Leksi lain yang tinggal di sana. Yang jelas, perlawanan melawan penindasan dari satu pihak terhadap pihak lain harus terus diperjuangkan.
Novel ini sarat akan pesan kritik sosial, menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca. Penulis mengambil sudut pandang dari setiap tokoh dalam novel Tanah Tabu ini sehingga pembaca tidak hanya melihat kejadian dari satu sudut pandang narator. Lebih kerennya lagi, penulis tidak hanya meletakkan manusia sebagai narator, pembaca tidak akan menyadari sebelum sampai di akhir cerita bahwa kisah kehidupan Mabel dan keluarganya juga diceritakan oleh tokoh yang bukan manusia. Namun pengambilan sudut pandang yang berganti-gantian acap kali membuat pembaca lupa siapa yang sedang bercerita.
Gaya bercerita yang unik, komposisi yang menarik, juga urgensi masalah menjadikan Tanah Tabu juara pertama dalam Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2008, dengan dewan juri diantaranya dua sastrawan cum jurnalis kondang Linda Christanti dan Seno Gumira Ajidarma, sehingga tentu saja novel ini layak dan bagus untuk dimasukkan dalam daftar baca anda.

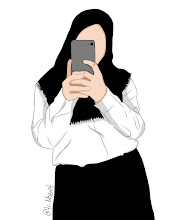





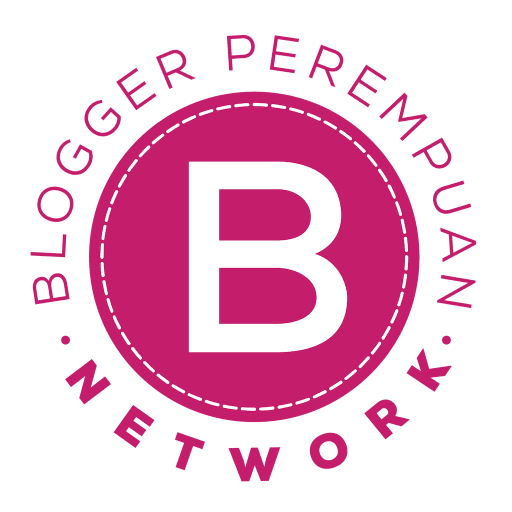
0 komentar: