Angin bertiup kencang ketika aku memarkirkan sepeda motorku di depan sebuah rumah, yang terletak tepat berseberangan dengan Pura Jagatnatha. Awan berubah menjadi abu-abu mengiringi doa-doa yang terus dipanjatkan sulinggih di halaman luar pura.
Pura Jagatnatha adalah satu-satunya pura di Pekanbaru. Terletak di Jalan Rawa Mulya tak Jauh dari Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.
Salah seorang di antara mereka memukul-mukul kentongan bambu dengan keras di depan sesajen. Alunan gamelan yang ditabuh Sekaa Gong mendayu-dayu mengiringi jalanya upacara. Sekaa Gong adalah para penabuh gamelan dan instrumen sakral umat Hindu.
Kentongan juga terus dibunyikan di Balai Kul-Kul sebagai pertanda untuk memanggil umat Hindu di sekitar Pura untuk melangkahkan kakinya ke rumah ibadah.
Sedangkan di belakang pemain Sekaa Gong, patung setinggi dua meter dengan wajah mengerikan bertelanjang dada dan membawa sebuah koper. Itu lah Ogoh-ogoh yang akan diarak. Ogoh-ogoh adalah perwujudan makhluk mitologi dari Bali yang diceritakan memiliki wajah seram, simbol kejahatan, dan sifat buruk manusia.
Angin kencang bertiup semakin kencang menerbangkan debu-debu jalanan juga daun-daun dari atas pohon. Tikar tempat duduk sulinggih pun sempat terlipat ditiup angin. Hujan deras turun tepat setelah selesainya ritual.
Aku segera berteduh menuju salah satu balai di halaman dalam satu-satunya pura yang ada di Pekanbaru ini. Duduk bersama Sekaa Gong kemudian berpindah ke Balai sebelahnya. Tak elok anak perempuan duduk bersama para laki-laki apa lagi cuma berdua dengan Sofi.
Di balai yang tak berdinding ini aku mengobrol dengan beberapa wanita Hindu yang mengikuti ritual arak-arakan ogoh-ogoh. Melihat upacara ini, aku seperti merasa di Bali meskipun aku melihat Bali hanya dari layar kaca.
Para pria memakain penutup kepala khas Bali yang disebut dengan udeng, baju safari dan sarung yang dipakai hingga kira-kira tujuh senti di atas mata kaki yang juga dikenal dengan kamen. Tak lupa kain selendang yang diikatkan di pinggang. Sedangkan para wanita memakai kain kebaya atau kain sejenis brokat atau katun lengkap dengan selendang yang juga diikat di pinggang. Mereka juga menyanggul rambut dengan rapi.
Setelah hujan reda, kira-kira 15 anak laki-laki dan perempuan berpakaian hitam diberi masing-masing satu buah obor kemudian di sulut dengan api. Mereka berdiri berbanjar sebelum memasuki bagian dalam pura. Beberapa remaja perempuan membawa canang dan turut berbanjar di belakang anak-anak tersebut.
Untuk memasuki bagian dalam pura diharuskan memakai selendang yang diikatkan di pinggang, aku tidak memakai selendang karena kehabisan, tapi dengan izin meliput agenda tersebut aku diperkenankan memasuki bagian dalam pura. Sebelum masuk aku diperciki air dari mangkok berwarna coklat. “Ini buat syarat aja tidak apa-apa ya?” ujar Ketua Pelaksana arak-arakan ogoh-ogoh, Ketut Sujarwo karena mengetahui aku seorang muslim.
Setelah aku masuk ke bagian dalam yang juga sebuah halaman luas lengkap dengan bangunan suci khas pura, seorang pria paruh baya mengejarku dan menanyakan, apakah aku sedang haid atau tidak. Kujawab tidak dan dia bernapas lega. Katanya, perempuan haid di larang masuk pura bagian dalam.
Di dalam pura tersebut anak-anak dan remaja yang membawa obor dan canang tadi berkeliling mengitari pura selama beberapa kali, kemudian keluar melalui pintu lainnya. Setelah keluar mereka bergabung dengan umat lain dan bersiap mengarak ogoh-ogoh.
Ogoh-ogoh digotong oleh sembilan pemuda Hindu. Ogoh-ogoh diarak dengan berjalan kaki dari Jalan Rawa Mulya menuju Jalan Sudirman kemudian berbelok ke Jalan Arifin Ahmad dan kembali lagi ke Jalan Rawa Mulya menuju pura. Dari pura ke pura, kembali ke asal.
Di sepanjang jalan, pemuka Hindu mengucapkan doa-doa berbahasa Bali. Sesekali ia meneriakkan ‘Haar-Haar Mahadev’ yang kutahu dari film India berarti Hidup Mahadewa atau Dewa Siwa. Teriakan itu disambut dengan sorakan oleh umat Hindu yang mengikuti arak-arakan.
Lelah kakiku berjalan sepanjang jalan kenangan, tak kubayangkan lelahnya pemuda-pemuda yang mengusung ogoh-ogoh. Tak heran jika sebuah mobil pick up menyertai dan membawakan air mineral kemasan gelas. Sesekali pemuda bergantian membawa ogoh-ogoh. Beberapa kali mereka memutar-mutar ogoh-ogoh. Hingga memasuki Jalan Rawa Mulya, ogoh-ogoh tak mampu menahan pijakan karena digoncang terlalu keras, jatuh dan menggelinding lah kepala ogoh-ogoh.
Salah satu pemain Sekaa Gong, Badai mengatakan padaku, jika itu bukanlah hal yang disengaja. Tapi semata-mata karena penyangganya tidak kuat, ketika diputar-putar terjatuhlah ogoh-ogoh yang malang.
Kendati demikian, ogoh-ogoh tetap diputar-putar penuh semangat oleh pemuda-pemuda tersebut meski pun terjatuh lagi. Saat matahari tenggelam dan gelap menyapa, salah seorang pemuda memainkan obor yang dipegangnya, menyemburkan dengan minyak dan berkobarlah api tersebut.
Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya puluhan pasang mata dari tepi jalan mengawasi arak-arakan ini, beberapa anak kecil berkerudung turut menyertai dari berangkat hingga pulang. Alunan Sekaa Gong pun tak berhenti dimainkan.
Tiba di belakang pura, ogoh-ogoh diletakkan di dekat semak-semak sebelum dibakar. Pembakaran ini sebagai simbol hilangnya sifat-sifat buruk dan negatif manusia melalui ogoh-ogoh. Dengan terbakarnya ogoh-ogoh, amarah, kerakusan dan kesombongan ikut lenyap bersama ogoh-ogoh yang menjadi abu.
Lelah berjalan mengikuti arak-arakan ogoh-ogoh, seorang pria mempersilahkanku untuk mengambil minuman yang disediakan ketika aku duduk beristirahaat sambil menuliskan berita. Ada teh, kopi juga es yang menyegarkan. Melihat keragu-raguanku, pria tersebut menegaskan jika apa yang dihidangkan adalah halal. “Tenang aja, itu halal kok,” kata pria tersebut meyakinkanku.
“Boleh saya minum Pak?”
“Boleh, ambil aja,” jawabnya.
Akhirnya penatku hilang setelah dua gelas air es melewati tenggorokanku. Setelah pembakaran ogoh-ogoh, dilanjutkan dengan sembahyang di dalam pura. Dari balai tempatku duduk terdengar musik yang disebut musik Lelambatan, katanya biar konsentrasi dalam sembahyang. Aku tidak mengikutinya.
Keesokan harinya, saat Hari Raya Nyepi, umat Hindu akan berpuasa selama 24 jam dari jam 6 pagi hingga jam 6 pagi berikutnya. Kata I Gusti Gede Nyoman Wiratama, mereka akan melakukan catur barata penyepian atau ngambek geni. Yaitu tidak menyalakan api (Amati Geni), tidak bekerja (Amati Karya), tidak bepergian (Amati Lelanguan) dan tidak bersenang-senang (Amati Lengangunan).
Ternyata umat hindu juga memiliki kebiasaan seperti Hari Raya Idul Fitri umat Islam. Jika Muslim menyebutnya halal bihalal, umat Hindu menyebutnya Dharma Santi. Acara berkumpul dan bermaaf-maafan serta berkunjung ke rumah-rumah.








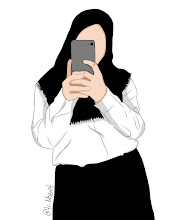





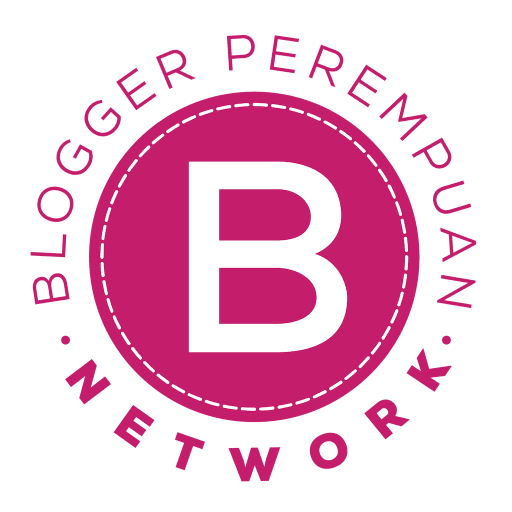
0 komentar: